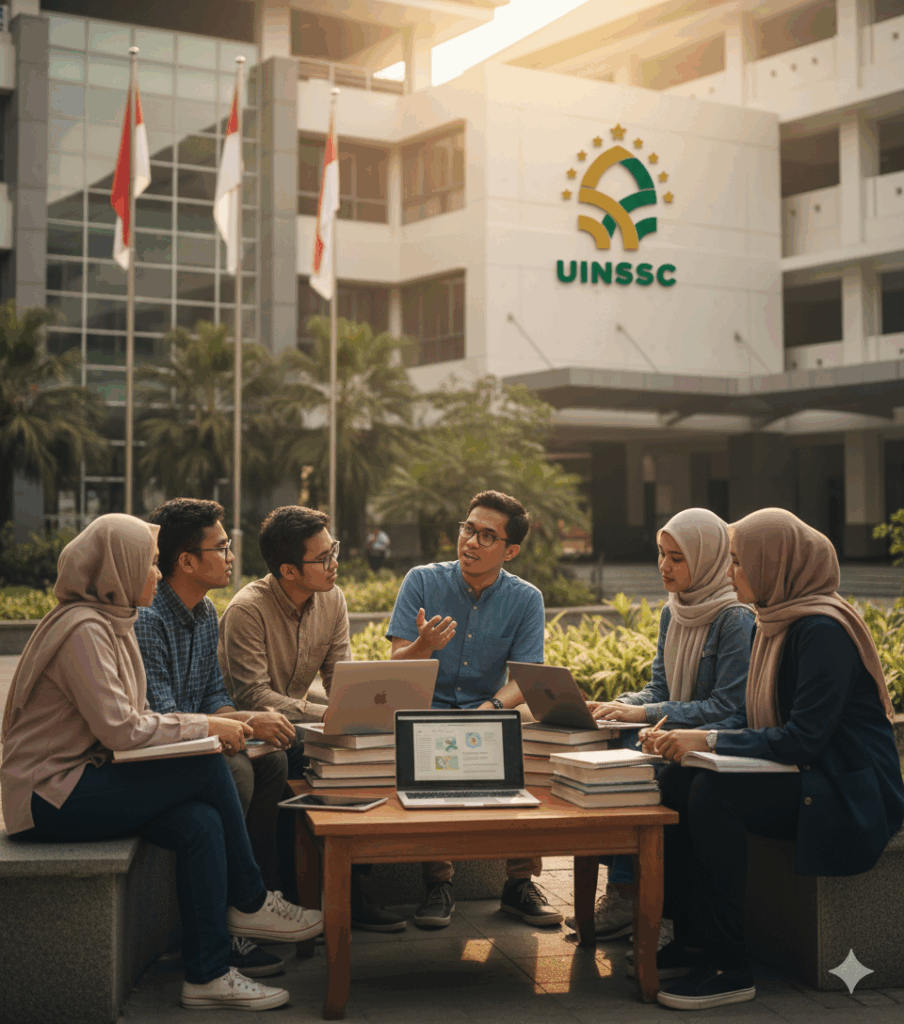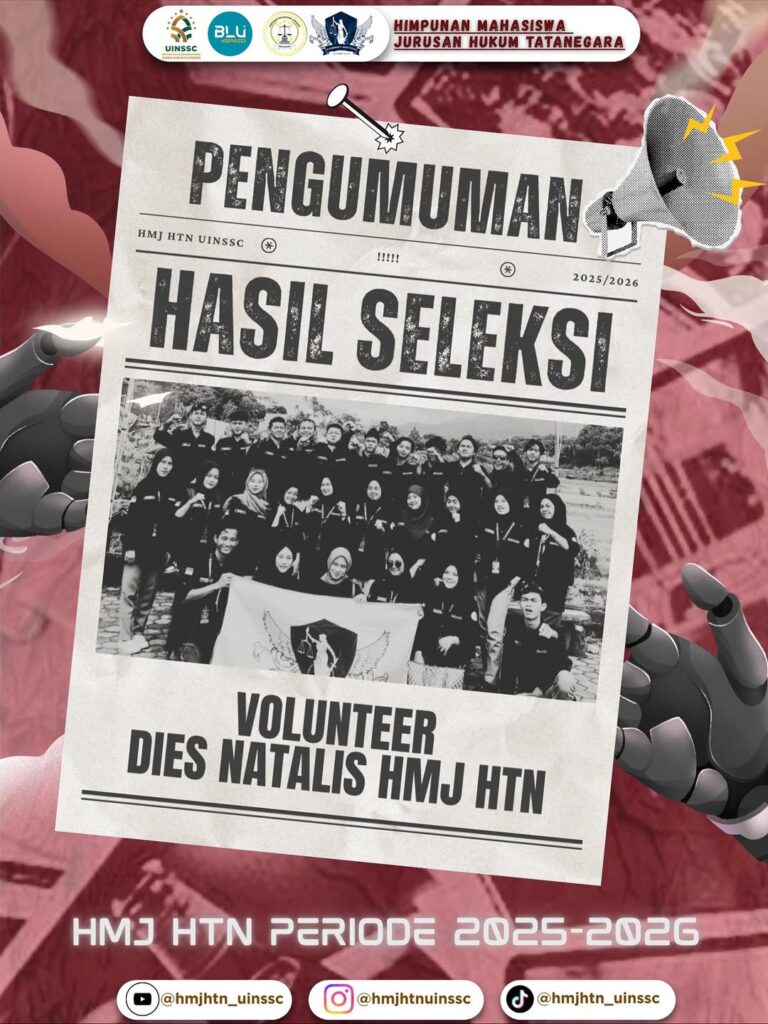Media sosial hari ini telah menjadi ruang baru bagi mahasiswa untuk berbicara, berdebat, dan mengekspresikan gagasan. Namun di tengah kebebasan itu, batas antara argumentasi dan provokasi sering kali kabur. Mahasiswa Hukum Tata Negara Islam (HTNI) seharusnya mampu tampil sebagai penjernih di tengah bisingnya opini publik, bukan sekadar penggemar keramaian digital. Tugas utama mahasiswa bukan memperbanyak suara, melainkan memperdalam makna dari setiap kata yang diucapkan.
Dalam konteks keislaman, tradisi berpikir kritis sudah lama hidup. Para ulama terdahulu berbeda pendapat tanpa saling menegasikan satu sama lain. Itulah warisan intelektual yang seharusnya dihidupkan kembali di ruang publik modern: berpikir tajam tanpa kehilangan adab, berani berpendapat tanpa kehilangan arah. Di sinilah nilai akademik mahasiswa diuji — bukan seberapa lantang berbicara, tapi seberapa kuat landasan pikirannya.
Mahasiswa HTNI memiliki modal penting: pemahaman tentang hukum, etika, dan nilai-nilai Islam. Ketiganya menjadi kompas dalam menavigasi dunia digital yang rawan bias, hoaks, dan manipulasi opini. Dengan bekal itu, mahasiswa bisa menjadi filter moral yang menjaga agar ruang publik tidak berubah menjadi arena saling menjatuhkan. Suara mereka penting, bukan karena keras, tetapi karena jernih.
Agar nalar tetap sehat, mahasiswa perlu terus membaca, menulis, dan berdiskusi lintas pandangan. Semangat intelektual bukan hanya tentang menolak, tetapi juga merumuskan alternatif. Suara mahasiswa HTNI seharusnya menjadi energi pemikiran yang mendorong perbaikan—tidak melalui slogan, tapi melalui gagasan yang lahir dari refleksi dan tanggung jawab ilmiah.
CATATAN PENTING
Tulisan diatas adalah hasil generative AI. Bukan tulisan sebenarnya dari sivitas.
ini dibuat untuk kebutuhan dummy website.